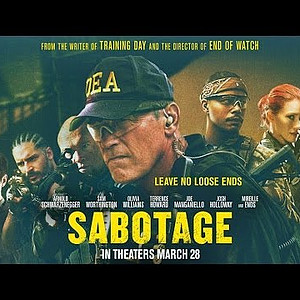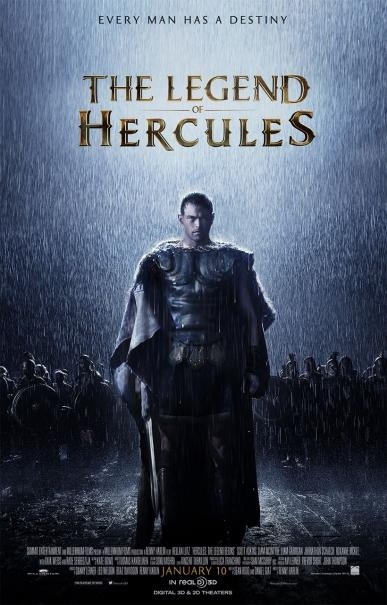Tagline meyakinkan, trailer mempesona, artis utama terkenal; tapi.. semuanya hanya bertahan sampai “4th wave” alias gelombang ke-4. The 5th wave ternyata adalah sebuah cerita tentang kiamat yang membosankan, dan sepertinya dibuat khusus untuk anak-anak dan remaja. Ide ceritanya sendiri terlalu mirip dengan The Host karya Stephanie Meyer.
Bercerita bahwa muncul sebuah kapal luar angkasa yang super besar dan mengitari bumi; lantas kapal tsb mengeluarkan gelombang pertama, yang mematikan seluruh listrik & mesin di bumi. Gelombang ke-2 adalah tsunami. Gelombang ke-3 adalah wabah flu burung. Gelombang ke-4 adalah mereka seperti parasit yang bisa masuk dan mengendalikan manusia. Dengan ke-4 gelombang yang nyaris membuat manusia punah, maka manusia yang tersisa sangat ketakutan dengan gelombang ke-5 — yang entah apa.
*SPOILER ALERT!!!* *SPOILER ALERT!!!* *SPOILER ALERT!!!*
Lanjutan ceritanya, Cassie (Chloe Grace-Moretz) yang mengungsi di kamp bersama Ayah dan adiknya akhirnya diselamatkan oleh Angkatan Darat yang memboyong anak-anak duluan demi alasan keselamatan. Ternyata malah Angkatan Darat tsb menyerang dan membunuh semua pengungsi, aneh bukan? Jika belum cukup mencurigakan dan membongkar cerita; lantas anak-anak tersebut disuntik oleh pelacak dan dilatih untuk menjadi prajurit. Anak-anak? jadi prajurit? Masuk akal kah manusia yang putus asa sempat-sempatnya melatih anak-anak untuk berperang?
Nah, ketika semua plot terbuka, bahwa pelacak tsb justru yang membuat mereka melawan manusia yang tidak dihinggapi parasit; ceritanya jadi semakin tidak masuk akal. Alasan mereka menggunakan anak-anak adalah karena mudah dimanipulasi. Pertanyaan besarnya: Jika alien tsb dengan canggih mampu mendatangkan gelombang elektromagnet, tsunami, wabah burung, bahkan sampai menyusup; untuk apa susah-susah menggunakan anak-anak untuk melawan manusia yang tersisa? Tidak cukup hebatkah mereka?
Dalam hal cerita, The 5th Wave masih kalah jauh dengan Stephanie Meyer. Bahkan dramanya saja cukup memuakkan. Ketika seorang gadis sudah hampir mati, muncullah pria ganteng yang memiliki kemampuan super karena ia adalah separuh alien. Tidak adakah alur cerita yang lebih tidak mudah tertebak? Efek visualnya sebenarnya tidak terlalu buruk; tapi dengan cerita yang tidak bermutu, film ini jadi terasa hambar. Nilai 4/10 @ristiirawan.