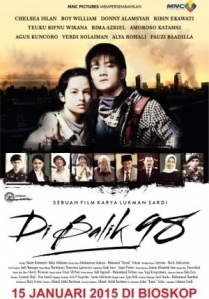Lemme recap the 1st film for you! The Kissing Booth, film pertamanya adalah salah satu dari film teen rom-com yang membuatku merasakan euforia setelah menontonnya. Senang karena melihat para pemerannya yang enak dipandang mata. Joey King sebagai Elle yang bersahabat dengan Lee (Joel Courtney) karena lahir di tanggal yang sama dan orang tua mereka bersahabat baik. Tentu ceritanya bisa ditebak, karena Elle akhirnya jatuh hati dengan kakak Lee, Noah (Jacob Elordi) yang super HOT, idola banyak wanita. Perasaan mereka terungkap gara-gara mereka membuka “Kissing Booth” alias stan jasa ciuman untuk proyek sekolah Elle & Lee (yang tidak mungkin terjadi di Indonesia ~ dan sekarang di seluruh dunia, karena pandemi covid-19 ini!). Elle melanggar satu dari aturan persahabatannya dengan Lee; tetapi mereka akhirnya bisa berdamai, bahkan Lee menemukan pacar sendiri Rachel (Meganne Young) berkat “Kissing Booth” juga. Di akhir film, Elle melepas Noah yang berangkat kuliah ke Harvard.

Di sekuelnya, The Kissing Booth 2, Elle sedang insecure karena LDR (Long Distance Relationship) dengan Noah. Ketika Noah menawarinya untuk lanjut kuliah di Harvard, Elle senang tapi galau karena ia dan Lee punya janji sejak kecil untuk kuliah bersama di UC Berkeley. Demi mendapatkan uang tunai untuk biaya kuliah, Elle mengikuti kompetisi Dance Dance Revolution (DDR) dengan bantuan teman barunya, Marco (Taylor Zakhar Perez) yang tidak kalah ganteng dari Noah. Di sisi lain, Elle tidak menyadari bahwa ia menjadi pengganggu dalam hubungan Lee dengan Rachel.
Film pertamanya memang tidak terlalu kuat dalam segi cerita, tetapi berhasil membangkitkan rasa “gemas” karena bumbu-bumbu percintaan remaja yang disertai dengan kecorobohan mereka yang lucu (seperti Elle pakai rok kesempitan, dan Elle yang ngumpet di bawah ranjang Noah); tetapi film kedua ini justru kehilangan “greget”nya. Ceritanya sendiri memang sesuai dengan perkembangan umur karakternya, di mana Elle sedang berusaha mencari jati diri untuk menentukan kuliahnya; dan Noah yang menghadapi dunia kuliah yang tidak sama seperti SMA.
Di film kedua ini, Elle menjadi lebih “berisik” daripada film pertamanya, dan itu mengganggu. Film kedua terlalu bersusah-payah menyambung cerita dengan film pertama dan meniru kejutan-kejutan yang sama, sehingga otomatis sudah tidak seru lagi. Terlalu dipaksakan dan aneh ketika “Stan Ciuman” kembali diadakan, tetapi akhirnya juga hanya sebagai properti untuk menunjang kampanye LGBT, yang ceritanya sendiri tidak ada hubungannya dengan cerita utama! Sebut saja adegan teman Elle (yang aku sendiri sampai tidak ingat siapa namanya, karena tokohnya sebenarnya tidak penting!) yang comes up saat di Kissing Booth; adegan yang terlihat garing dan palsu.
Pemilihan DDR sebagai ajang kompetisi yang mengesampingkan “Kissing Booth” sendiri juga terasa kurang relevan dengan kondisi sekarang. Meskipun tidak dipungkiri, dance mereka sangat keren, para remaja pasti terpesona sama Taylor Z Peres. Bumbu yang baru dalam film kedua ini, tetapi membuat sutradara kehilangan fokus. Sejak kapan The Kissing Booth berubah menjadi film dance? Banyak adegan yang “nanggung” karena usaha penulis & sutradara untuk keluar dari klise tetapi malah membuat gelora film ini hilang. Durasi 131 menit juga terlalu panjang (lebih panjang 20 menit dari film sebelumnya).

The Kissing Booth 2 akan terasa menyenangkan ditonton jika memang kamu memiliki emotional attachment dengan para tokohnya dari prekuelnya atau suka melihat yang manis-manis. Bagaimana hati kita tidak meleleh, melihat Jacob Elordi seperti ini?

Selain eye candy ini, ada sisi positif yang bisa dipelajari dalam film ini, bahwa 1) kita harus kontrol emosi, belajar mendengarkan orang lain agar kita tidak terjebak dalam asumsi kita sendiri. 2) belum tentu yang kita anggap baik untuk orang lain, lalu kita tutupi, tidak akan membawa masalah lebih besar.
Kuberikan rating 6/10!